Konsep Perilaku Pada Level Kelompok
Oleh: Djamal S. Askar, Muhammad Nasri Dini, Sulaeman
Mahasiswa Pascasarjana S2 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Surakarta
PENDAHULUAN
Perilaku organisasi pada hakikatnya bertumpu pada ilmu
perilaku itu sendiri, yakni bidang yang berfokus pada pemahaman terhadap
tindakan manusia di dalam organisasi. Studi ini menyoroti dua komponen penting:
individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku
tersebut. Dengan kata lain, organizational behavior adalah studi tentang
bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam suatu sistem sosial yang
terstruktur, serta bagaimana organisasi itu memengaruhi dan dipengaruhi oleh
perilaku manusia.
Seperti yang dikemukakan oleh Kelly dalam karyanya Organizational
Behavior, perilaku organisasi memuat interaksi dan hubungan timbal balik
antara organisasi dan individu. Tujuan akhirnya adalah mengarahkan perilaku
manusia agar selaras dengan pencapaian tujuan bersama. Stephen P. Robbins juga
mendefinisikan organisasi sebagai unit sosial yang terdiri atas dua orang atau
lebih yang secara sengaja diatur untuk mencapai sasaran tertentu secara
berkesinambungan.
Dalam konteks ini, perilaku tidak sekadar dipahami sebagai tindakan,
tetapi juga mencakup cara berpikir (way of thinking or behaving).
Robbins memandang organizational behavior sebagai bidang kajian tentang
dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi,
dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi.
Di era modern, kemajuan teknologi, kompetisi global, dan dinamika sosial
menuntut kerja sama lintas disiplin dan lintas departemen. Pemikiran kolektif
terbukti lebih kuat dibanding pemikiran individual. Karena itu, membangun
sebuah tim menjadi kunci penting dalam keberhasilan organisasi. Proses team
building mencakup seleksi, pengembangan, pelatihan, dan fasilitasi agar
setiap anggota mampu bekerja menuju tujuan bersama dengan motivasi dan
kebanggaan.
Seorang team builder idealnya dapat memenuhi dua tuntutan utama:
pertama, hasil kerja yang berkualitas dan tepat waktu; kedua, pemenuhan
kebutuhan psikologis anggota agar merasa adil dan terhindar dari konflik.
Kolaborasi dan saling berbagi pengetahuan menjadikan tim mampu menyelesaikan
pekerjaan lebih efektif daripada individu. Dalam pengertian Robbins, a team
is a group organized to work together to accomplish a set of objectives that
cannot be achieved effectively by individuals.
Tim dapat bersifat permanen (natural teamwork) atau temporer (cross-functional
action team). Bentuk yang paling maju disebut self-directed team,
yaitu kelompok yang bekerja secara mandiri dengan tingkat otonomi tinggi dan
pengawasan minimal.
Banyak organisasi kemudian menjadikan pembangunan tim sebagai bagian
dari strategi organizational development. Kelompok dan tim memang dua
konsep berbeda. Kelompok (group) sekadar kumpulan individu yang
berinteraksi untuk berbagi informasi atau membantu dalam lingkup kewenangan
masing-masing, tanpa sinergi kolektif. Sebaliknya, tim menghasilkan positive
synergy melalui koordinasi yang terarah. Upaya individu di dalamnya menyatu
menghasilkan kinerja kolektif yang lebih besar daripada sekadar jumlah
kontribusi masing-masing anggota.
KONSEP PERILAKU TIM
Tim kerja merupakan jantung dari efektivitas organisasi modern. Robbins
dan Judge (2008) menjelaskan bahwa tim kerja adalah kelompok yang usaha
individunya menghasilkan kinerja yang lebih tinggi daripada akumulasi masukan
per individu. Hal ini berarti, sinergi tim memberikan hasil yang melampaui
kemampuan anggota jika bekerja sendiri.
Allen (2004) menggambarkan anggota tim sebagai pribadi yang sportif,
sensitif, dan mudah bergaul, dengan kemampuan membaca dinamika emosional
kelompok secara mendalam. Mereka bekerja secara terkoordinasi sehingga tercipta
sinergi positif. Daft (2003) menambahkan bahwa team adalah unit yang
terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berkoordinasi
dalam menyelesaikan tugas spesifik.
Katzenbach dan Smith memandang tim sebagai sekelompok kecil orang dengan
keterampilan saling melengkapi dan komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama.
Hunsaker mempertegas, bahwa kerja tim merupakan kolaborasi dengan efisiensi
tinggi yang didorong oleh kepercayaan dan tanggung jawab bersama.
Dalam membangun tim, terdapat beberapa komponen dasar. Pertama,
keberadaan minimal dua individu yang berinteraksi secara rutin. Kedua, adanya
tujuan kinerja yang sama, yang menyatukan mereka dalam semangat kolektif. Tanpa
interaksi dan tujuan bersama, kelompok tersebut tidak dapat disebut sebagai
tim.
Manfaat kerja tim sangat nyata: beban kerja menjadi lebih ringan,
semangat kebersamaan meningkat, dan produktivitas organisasi pun bertambah. Tim
juga memungkinkan efisiensi waktu serta inovasi yang lebih cepat. Popularitas
kerja tim dalam organisasi meningkat karena beberapa alasan. Kinerja tim
terbukti lebih unggul dari individu, serta lebih adaptif terhadap perubahan
yang cepat. Tim dapat dengan mudah dibentuk, dibubarkan, dan diarahkan kembali
sesuai kebutuhan organisasi.
Robbins mengelompokkan tipe-tipe tim menjadi empat:
- Problem solving team, yaitu kelompok
dalam departemen yang rutin membahas cara meningkatkan kualitas,
efisiensi, dan lingkungan kerja.
- Self-managed work team, kelompok yang
mengerjakan pekerjaan saling terkait dan bertanggung jawab secara langsung
atas hasilnya tanpa pengawasan intensif.
- Cross-functional team, yang terdiri
dari karyawan lintas fungsi dan departemen untuk menangani tugas tertentu.
- Virtual team, yaitu tim yang
memanfaatkan teknologi digital untuk berkolaborasi jarak jauh demi tujuan
bersama.
TEAM EFFECTIVE
Membangun kerja sama dalam tim yang solid dan efektif bukan perkara
mudah. Keberhasilan tim sangat bergantung pada fondasi nilai yang dibangun di
dalamnya. Salah satu kunci utama adalah memiliki visi dan misi yang sama. Tanpa
kesamaan arah, kerja tim akan terpecah, seperti seseorang ingin menuju utara
sementara lainnya memilih selatan. Karena itu, kesamaan visi dan misi menjadi
landasan yang mengikat seluruh anggota.
Rasa saling percaya juga merupakan prasyarat mutlak. Tanpa kepercayaan,
setiap anggota akan bekerja sendiri-sendiri, kehilangan semangat kolektif, dan
merusak ritme kerja. Kepercayaan membuat anggota yakin bahwa rekan-rekannya
akan menunaikan tanggung jawab dengan baik.
Selain itu, komunikasi yang intensif menjadi penopang utama. Ketika
komunikasi tersumbat, koordinasi terganggu dan tujuan tim tidak akan tercapai.
Oleh karena itu, komunikasi harus dibangun melalui pertemuan rutin maupun
melalui aplikasi digital seperti WhatsApp atau Line. Yang
terpenting bukan medianya, melainkan keterbukaan antaranggota.
Tim yang solid juga perlu memperkuat hubungan personal di luar konteks
pekerjaan. Aktivitas seperti makan siang bersama, olahraga, atau kegiatan
sosial dapat mempererat chemistry dan menumbuhkan rasa saling memahami.
Selanjutnya, sistem penghargaan menjadi pendorong motivasi. Pemberian reward
tidak hanya mengakui prestasi individu, tetapi juga menumbuhkan semangat
kolektif. Bentuk penghargaan bisa sederhana, seperti “karyawan terbaik bulan
ini” atau bonus atas kontribusi luar biasa. Prinsipnya, setiap usaha patut
diapresiasi agar semangat tim tetap menyala.
Pemahaman peran dan tanggung jawab juga sangat penting. Seperti dalam
tim sepak bola, tidak semua bisa menjadi penyerang atau penjaga gawang. Setiap
anggota harus memahami fungsinya dalam struktur tim. Kesadaran ini membantu
fokus dan efisiensi dalam bekerja.
Kompetensi pun perlu terus ditingkatkan. Ketika kemampuan antaranggota
terlalu berbeda, ketimpangan bisa menghambat produktivitas. Karena itu,
pelatihan dan pengembangan kompetensi harus menjadi bagian dari budaya
organisasi.
Saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat adalah tanda
kedewasaan dalam tim. Perbedaan justru memperkaya ide dan solusi. Dengan sikap
saling menghormati, perbedaan tak akan memecah belah, melainkan memperkuat
kohesi sosial dalam kelompok.
Selain itu, komitmen kuat dari setiap anggota menjadi fondasi utama. Tim
yang solid tidak akan berjalan baik bila sebagian anggotanya kehilangan
semangat. Ketika satu orang melemah, yang lain harus memberi dukungan. Komitmen
bersama menjadikan tim tangguh dalam menghadapi tantangan.
Akhirnya, evaluasi rutin menjadi langkah penting untuk menjaga
efektivitas kerja tim. Evaluasi bukanlah sarana mencari kesalahan, melainkan
kesempatan untuk refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Dari sinilah tim dapat
menilai keberhasilan, memahami kekurangan, dan menyusun strategi baru secara
bersama-sama.
LEADERSHIP OF GROUP
Dalam setiap organisasi yang membutuhkan kerja sama manusia,
kepemimpinan selalu menjadi unsur paling penting. Namun, perhatian terhadapnya
sering kali kurang memadai. Perkembangan konsep kepemimpinan bergerak dari yang
bersifat pra-ilmiah, yang mengandalkan intuisi dan bakat alami, menuju
kepemimpinan ilmiah yang berbasis analisis, fungsi, dan situasi.
Pada tahap awal, kepemimpinan dianggap sebagai anugerah atau bawaan
lahir yang dimiliki seseorang. Pandangan ini kemudian bergeser menjadi
pemahaman bahwa kepemimpinan bukanlah kedudukan, melainkan fungsi sosial.
Kepemimpinan efektif ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap situasi dan
hubungan antarindividu.
Pemimpin modern tidak lagi sekadar pengambil keputusan, melainkan
pelatih (coach) dan koordinator yang membantu kelompok belajar dan
bekerja lebih efisien. Tugas utama seorang pemimpin adalah menciptakan iklim
sosial yang baik. Jika pemimpin memperlakukan dirinya sebagai supervisor
yang “merajai” bawahan, suasana kerja akan menjadi kompetitif, penuh jarak, dan
saling menyalahkan. Sebaliknya, pemimpin yang menumbuhkan rasa saling
menghormati akan menciptakan suasana persaudaraan dan kebebasan, sehingga
anggota merasa memiliki tanggung jawab kolektif.
Pemimpin juga berperan dalam membantu kelompok mengorganisasikan diri,
menetapkan tujuan, serta membagi tanggung jawab. Ia berfungsi sebagai “ahli
prosedur” yang memastikan proses kerja berjalan efisien tanpa menghilangkan
nilai-nilai demokratis. Dalam menjalankan perannya, pemimpin tidak boleh
memonopoli keputusan, tetapi membimbing kelompok untuk belajar mengambil
keputusan sendiri. Dengan begitu, kelompok akan berkembang menjadi dewasa dan
bertanggung jawab.
Selain itu, pemimpin yang efektif memberi kesempatan kepada kelompok
untuk belajar dari pengalaman. Evaluasi bukan hanya pada hasil, tetapi juga
pada proses. Dengan refleksi, kelompok dapat menilai cara kerja mereka secara
jujur dan obyektif, lalu memperbaikinya untuk mencapai kinerja yang lebih baik
di masa depan.
KONSEP LEARNING ORGANIZATION (LO)
Learning organization atau organisasi pembelajar merupakan
entitas yang mendorong setiap individu untuk terus belajar dan memperluas
kapasitas diri, agar organisasi mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan
zaman. Menurut David A. Garvin (2000), organisasi pembelajar adalah organisasi
yang terlatih menciptakan, memindahkan, dan mengelola pengetahuan, serta
memodifikasi perilaku berdasarkan wawasan baru. Peter Senge juga menegaskan
bahwa organisasi pembelajar adalah tempat di mana orang senantiasa
mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang mereka kehendaki.
Organisasi pembelajar lahir dari kesadaran bahwa keunggulan kompetitif
di era global hanya bisa dicapai jika organisasi mampu bertransformasi melalui
pembelajaran berkelanjutan. Tujuan utamanya bukan sekadar mempertahankan
eksistensi, melainkan terus-menerus memperbaiki diri dan memperluas potensi.
Peter Senge menyebut lima disiplin utama yang menjadi pilar learning
organization:
Pertama, personal mastery atau penguasaan pribadi. Ini
mencerminkan kemampuan individu untuk memperdalam visi pribadi, memfokuskan
energi, serta melihat realitas dengan jernih. Dalam organisasi, hal ini
menciptakan budaya belajar yang menumbuhkan kesabaran dan komitmen pada tujuan.
Kedua, mental model atau pola pikir. Disiplin ini mengajarkan
pentingnya refleksi atas cara berpikir dan tindakan. Individu dan organisasi
diajak untuk memahami bagaimana keyakinan dan asumsi memengaruhi keputusan.
Ketiga, shared vision atau visi bersama. Visi yang dibangun
secara kolektif akan mengikat anggota dalam komitmen bersama. Ia bukan sekadar
dokumen formal, tetapi gambaran masa depan yang menyalakan semangat kolektif.
Keempat, team learning atau belajar bersama. Proses ini
menekankan percakapan mendalam dan berpikir kolektif yang melampaui kemampuan
individu. Melalui interaksi terbuka, tim dapat mengembangkan kecerdasan
kolektif yang lebih besar dari jumlah anggotanya.
Kelima, systems thinking atau berpikir sistemik. Ini merupakan
kerangka konseptual yang memungkinkan organisasi memahami hubungan antarbagian
dan mengelola perubahan secara menyeluruh. Tanpa berpikir sistem, pembelajaran
organisasi akan terfragmentasi dan tidak efektif.
Argyris dan Schön membedakan dua jenis pembelajaran organisasi: single-loop
learning dan double-loop learning. Single-loop learning
adalah pembelajaran yang berfokus pada perbaikan kesalahan dalam kerangka nilai
dan norma yang sudah ada, sedangkan double-loop learning menuntut
perubahan nilai dan strategi yang mendasari perilaku organisasi.
Selain itu, dikenal pula deutero learning (pembelajaran tentang
cara belajar) dan anticipatory learning, yaitu pembelajaran yang
berorientasi pada masa depan melalui perencanaan strategis. Semua jenis
pembelajaran ini bertujuan menciptakan organisasi yang tanggap, reflektif, dan
berorientasi inovasi.
KONSEP PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC)
Menurut Johar Permana dan Asep Suryana (2016), Professional Learning
Community (PLC) adalah proses akuisisi pengetahuan melalui kolaborasi dan inquiry
untuk memecahkan masalah yang muncul dari praktik kerja sehari-hari. PLC
mendorong budaya belajar kolektif di lingkungan sekolah, sehingga terbangun
budaya mutu yang berkelanjutan.
PLC mengandung lima domain utama: professional culture, leadership,
focus on students, focus on professional learning, dan performance
and development. Andy Hargreaves menambahkan bahwa PLC memerlukan budaya
profesional yang ramah, suportif, penuh rasa hormat, dan saling percaya.
Dukungan organisasi seperti waktu, tempat, dan sumber daya menjadi faktor
penting agar PLC berkelanjutan.
Tujuan utama PLC di sekolah adalah memperbaiki strategi pembelajaran
secara berkesinambungan, menumbuhkan kepercayaan diri guru, membantu siswa
mencapai kompetensi tinggi, dan membangun kepemimpinan yang efektif. Dalam
praktiknya, PLC diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan kolaboratif seperti
KKG dan MGMP di sekolah.
Guru-guru berdiskusi tentang keberhasilan dan hambatan pembelajaran,
menganalisis data capaian siswa, serta merancang strategi perbaikan. Siklus ini
mencakup refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi berkelanjutan. Kepala
sekolah berperan penting sebagai fasilitator dan penggerak supervisi akademik
untuk memastikan setiap guru terlibat aktif dalam proses tersebut.
Salah satu bentuk konkret PLC adalah lesson study. Menurut Dindin
Abdul Muiz Lidinillah, lesson study merupakan model pembinaan profesi
guru melalui kajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan
berdasarkan prinsip mutual learning. Proses ini melibatkan tiga tahap:
perencanaan (plan), pelaksanaan (do), dan refleksi (see).
Dalam lesson study, guru bekerja sebagai tim untuk
mengidentifikasi masalah pembelajaran, merancang rencana, mengobservasi
pelaksanaan, lalu merefleksikan hasilnya. Pendekatan ini menumbuhkan budaya
reflektif, kolaboratif, dan kritis di kalangan guru. Seperti diungkapkan oleh
Dennis Sparks (1999), lesson study adalah proses kolaboratif yang
memungkinkan guru belajar bersama melalui pengalaman langsung di kelas.
Fokus utama dari PLC dan lesson study adalah membangun kesadaran
profesional bahwa guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Darling-Hammond
(1993) menegaskan bahwa komunitas belajar profesional mendorong guru untuk
saling mengobservasi, berdiskusi, dan merefleksikan praktik mengajar. Dengan demikian,
guru tidak lagi bekerja sendiri, melainkan dalam jejaring kolegial yang saling
menguatkan.
PLC yang kuat mampu mengubah budaya sekolah. Ia membentuk hubungan
fungsional yang kolaboratif, mendorong refleksi bersama, dan mengembangkan
semangat saling percaya. Ketika guru terbiasa bekerja dalam tim, mereka dapat
mengubah hambatan menjadi peluang dan menjadikan keberhasilan siswa sebagai
fokus utama.
KAJIAN HASIL RISET PERILAKU KELOMPOK
Berbagai penelitian telah menunjukkan pentingnya kerja tim,
kepemimpinan, dan pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kinerja.
Penelitian Desvi Intan Khairani, Candra Wijaya, dan Edi Saputra (2018) di SMA
Kecamatan Medan Labuhan menemukan hubungan positif antara kerja tim dan
komitmen guru dengan efektivitas kinerja. Semakin baik sinergi dan komitmen
dalam tim, semakin tinggi pula efektivitas kinerja guru.
Isti Fatonah (2013) menyoroti bahwa kepemimpinan pendidikan adalah
kemampuan memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Ia menekankan perlunya seleksi kepala sekolah yang akuntabel,
pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi melalui Penilaian Kinerja Kepala
Sekolah (PKS) agar kepemimpinan pendidikan berjalan efektif.
Masrukhin (2015) melalui penelitian di SMA NU Hasyim Asy’ari Kudus
menunjukkan bahwa penerapan strategi learning organization dapat
meningkatkan mutu dan daya saing lulusan. Dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan dan melakukan analisis SWOT, sekolah mampu menghasilkan strategi
yang adaptif terhadap tuntutan zaman.
Johar Permana (2016) juga menemukan bahwa pengembangan profesi guru
berbasis sekolah melalui PLC merupakan pendekatan paling relevan untuk
peningkatan kualitas pendidikan. Melalui kolaborasi, refleksi, dan pengembangan
berbasis pengalaman, guru dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya sekaligus
membangun budaya belajar yang berkelanjutan di sekolah.
DAFTAR PUSTAKA
Allen, R. (2004). Sportive and social sensitivity in teamwork.
London: Harper Business.
Daft, R. (2003). Organization theory and design (7th ed.).
South-Western College Publishing.
Garvin, D. A. (2000). Learning in action: A guide to putting the
learning organization to work. Harvard Business School Press.
Hunsaker, P. (2001). Training in team development. Boston:
McGraw-Hill.
Johar Permana, & Asep Suryana. (2016). Model pengembangan profesi
guru melalui professional learning community di sekolah menengah. Jurnal
Administrasi Pendidikan, XXIII(1).
Kelly, J. (1998). Organizational behavior. New York: McGraw-Hill.
Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993). The wisdom of teams:
Creating the high-performance organization. Harvard Business Press.
Masrukhin. (2015). Strategi membangun learning organization dalam
meningkatkan mutu dan daya saing lulusan. Jurnal Pendidikan Islam Quality, 3(1).
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). Perilaku organisasi
(R. Saraswati & F. Sirait, Trans.). Jakarta: Salemba Empat.
Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of
the learning organization. Doubleday.
Syamsu Q. Badu, & Novianty Djafri. (2017). Kepemimpinan dan
perilaku organisasi. Gorontalo: Ideas Publishing.
*) Tulisan ini sebelumnya disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Perilaku Organisasi

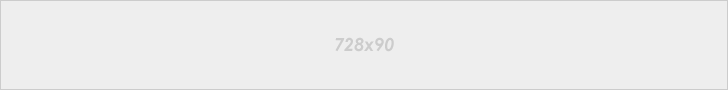




Tidak ada komentar